PELARIAN TANPA UJUNG
Apalagi
yang lebih sia-sia dari manusia selain kepiawaiannya menarik kesimpulan sendiri
?
Hidup
tiba-tiba saja seperti cuplikan gambar yang bergerak begitu pelan. Orang-orang
berlalu lalang, ada yang tertawa riang, ada yang berwajah tak senang. Dalam
kehidupan yang lebih terlihat seperti sebuah diorama bagiku kini, aku
memosisikan diri sebagai penonton. Menyaksikan orang-orang yang sibuk dengan
dunia mereka, menyisakan aku yang sibuk dengan duka nestapa.
Sesekali
mereka menyapu pandang padaku, mungkin terheran melihat seorang perempuan yang
duduk berjam-jam di sebuah kursi lorong utama kampus, menyumpal telinganya
dengan sumber suara yang berasal dari smarthphone
di pangkuan dan menatap tak karuan ke sekitar. Kepada mereka yang menaruh
beragam prasangka aku hanya melempar tatapan datar sembari berkata lemah dalam
hati. “Sudahlah lanjutkan saja aktivitasmu, jangan pedulikan aku.”
Setelah
malam kelabu yang meruntuhkan semua harapanku itu, hari-hariku terasa begitu
lama berlalu. Aku merasa terlalu buruk dalam segala hal. Aku kehilangan
kepercayaan diri dan terus menyalahkan diri sendiri. Aku kesulitan tidur, tidak
berselera dengan banyak hal dan berharap bisa mati rasa dalam sekejap.
Segalanya terasa begitu sulit, betapa patah hati bisa menjadi semenyebalkan
ini.
Dua
minggu sudah aku tidak bertemu Miko dan tentu saja tidak mengetahui kabarnya.
Setelah susah payah berdamai dengan diri sendiri aku memutuskan untuk berhenti
masuk kelas malam dan kuliah secara normal. Suasana kampus juga sudah cukup
membaik, senior-senior yang senang menunggui kami di depan pintu kelas itu kini
sudah cukup lelah dan masa bodoh. Jadi aku sudah tidak punya alasan lagi untuk
mengejar absensi di malam hari, dan juga aku harus mengambil jarak terlebih
dahulu. Jika semua ilusi itu berawal dari sebuah pelarian maka akan kuakhiri
pula dengan hal yang sama. Kadang manusia memang sangat lucu, kita seringkali
berlari dari satu hal yang menyebalkan untuk kemudian bertemu dengan hal
menyebalkan lainnya. Sambil berpikir begitu aku menarik napas panjang, mungkin
ini adalah saat yang tepat untuk menertawakan diri sendiri.
Meski
demikian tidak ada yang perlu disesali. Mengenal manusia sehangat Miko adalah
sebuah anugerah yang patut disukuri. Tidak pernah ada yang buruk dari semua
itu. Yang bermasalah hanya diriku sendiri, yang terlalu mudah terbang melayang
dan enggan menapak bumi. Yang membiarkan diri terjebak dalam ilusi. Yang tidak
mengantisipasi diri dan terlalu berani. Ah sudahlah, anggap saja itu semua
adalah risiko yang harus kuterima sebab terlalu mudah dimabuk cinta. Tetapi
kalau boleh jujur, semakin ke sini aku merasa semakin bodoh, sebenarnya tidak
ada hal buruk yang terjadi antara aku dan Miko, hubungan kami baik-baik saja
dan juga aku tidak pernah tahu dengan pasti sedekat apa ia dengan perempuan
luar biasa itu. Lalu kenapa aku harus melarikan diri ? Kenapa aku begitu senang
mengambil kesimpulan sendiri ? Kenapa aku seperti ini ? Tiba-tiba saja aku
merasa hampa dan putus asa.
Sungguh,
jatuh cinta itu sangat merepotkan. Ia tidak hanya membuatmu buta akan hal-hal
penting di sekitar tetapi juga menggerus akal sehatmu pelan-pelan. Ia tidak
peduli kau sudah melahap sekian banyak buku filsafat atau seberapa sering kau
mengkritik teman-teman mudamu yang menjadi budak asmara. Nyatanya, kau juga
sama, menjadi budak dari sebuah otoritas paling menyebalkan bernama rasa. Kalau
sudah begitu, apa kau masih bisa menyangkal ? Apa kau masih ingin terus berlari
? Jatuh cinta adalah sebuah kewajaran yang harus kau terima sepenuh hati sebab
itu adalah bagian paling jujur dari sifat alamiah manusia.
Meski
pada kenyataannya, setelah jatuh cinta yang begitu hebat itu aku kembali
menjadi seorang Anin yang frustasi dan kehilangan kepercayaan akan masa depan
dunia. Jika berada di sekitar Miko membuatku percaya pada banyak kebaikan dan
mimpi-mimpi baru bertumbuhan maka kini aku melihat dunia tak lebih dari
segudang sampah berserakan yang patut untuk dibersihkan. Tidak ada hal yang
menarik perhatianku sama sekali.
Dalam
perasaan yang nyaris hambar karena terlalu kecewa dengan diri sendiri, kulihat
senior perempuan berwajah jutek yang menghukumku pada hari pertama PMB tengah
mengejar-ngejar dosen dan berlalu lalang di depanku. Dengan kedua tangan yang
penuh oleh kantong belanjaan yang entah apa isinya, ia merayu dosen untuk perbaikan
nilai. Ternyata memang tidak banyak yang berubah, senior-senior adikuasa itu
tetap saja berlagak superior di depan mahasiswa baru tetapi merunduk dan
mengemis di depan dosen. Apa yang bisa diharapkan dari generasi muda yang
bermental pengecut seperti itu ?
Semester
pertama sebentar lagi berlalu dan semester selanjutnya akan tiba tak kalah
cepat. Tahun depan mahasiwa-mahasiswa baru kembali berdatangan. Pola-pola lama
akan kembali berulang. Hal-hal buruk terus diwariskan, yang berbeda hanya
pelaku dan yang dikenai perlakuan itu. Selebihnya sama saja, mental-mental
kolonial masih terus dilanggengkan diam-diam. Tidakkah mereka bosan dan
menginginkan perubahan ?
Rupanya
berada di lorong kampus ini seharian tidak akan pernah menyembuhkan patah
hatiku justru membuatnya semakin parah.
Dalam
keputusasaan yang berjangkit, mataku yang sejak tadi datar mengamati sekitar
beralih fokus pada dua orang sosok di depanku. Mereka tersenyum dan mengajakku
berinteraksi. Tiba-tiba saja aku merasa seperti seorang pencuri yang tertangkap
basah melarikan diri. Kedua orang itu menarik tanganku tanpa permisi. Aku
diseret menuju kantin samping musholla itu.
“Kamu
ke mana aja sih, kita mau bikin acara di Ruang Belajar,” dengan senyum yang
begitu tulus Vine berkata demikian. Aku ingin terharu tapi rupanya ada hal lain
yang lebih mengganggu.
“Dua
minggu terakhir aku bertanya-tanya, kamu kemana,” celaka, hatiku kembali
tersentuh oleh perasaan yang sebenarnya masih utuh.
Mereka
memperlakukanku seperti tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Sungguh, dua minggu
yang terlalu drama bagiku kini berakhir sia-sia.
Akankah
ini hanya pelarian tanpa ujung ?

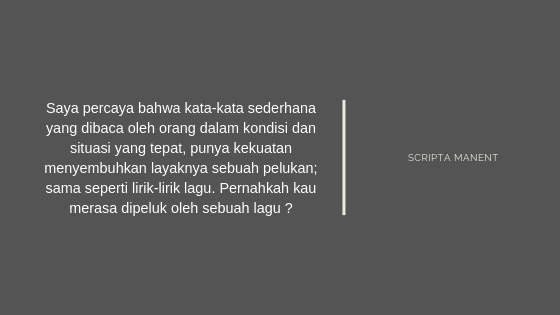


Komentar
Posting Komentar